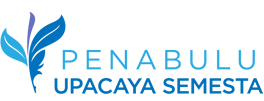Membicarakan demokrasi ekonomi, rasanya menarik buat disimak untuk mencari semacam kebersamaan pandangan dalam suasana yang dialogis. Ada beberapa catatan yang dapat dikemukakan sebagai bahan yang dapat kita diskusikan bersama.
Pertama, dari aneka bahasan di masa lampau, sering dibicarakan bahwa salah satu parameter dari demokrasi ekonomi dalam masyarakat adalah munculnya pemerataan pendapatan yang semakin baik. Pola redistribusi pendapatan yang bermakna keadilan lalu menjadi sorotan. Berkaitan dengan itu sering dipertanyakan kebijakan ekonomi dalam perspektif struktural: proses, perilaku, dan penataan hukum dan peraturan (law enforcement) yang menterjemahkan dan mendukung penerapan pemerataan secara luas.
Kedua, sering juga para ekonom saat kini mempersoalkan aspek pemerataan yang sering dengan pertumbuhan (redistribution with growth sebagaimana pengalaman Taiwan, Korea, dan Jepang). Dalam bahasan ini akan dikaitkan aspek the principles of resource allocation yakni alokasi sumber daya, sumber dana, dan sumber-sumber lainnya yang turut direkayasa untuk memacu pemerataan pendapatan yang di dalamnya juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Termasuk juga dipertanyakan tentang penataan harga dan perilaku pasar yang menggerakkan alokasi secara tepat, kontekstual dan relevan. Soal lainnya adalah penataan harga yang merangsang insentif ekonomis tetapi di dalamnya secara integralistik mengandung unsur keadilan dalam berekonomi.
Pandangan almarhum Moh. Hatta dan Kagawa dalam banyak hal adalah sama, bahwa koperasi harus dibangun mulai dari bawah dan kemudian harus menjadi besar.
Ketiga, dalam bahasan teori ekonomi saat kini sering kita mendengar ungkapan tentang normative economy dan positive economy: Positive economy mempersoalkan apa yang terjadi (actual condition). Sementara normative economy mempersoalkan what should be atau apa yang harus terjadi. Dan dalam sudut pandang normatif muncul pikiran kritis, muncul ruang mempersoalkan visi kita berekonomi. Sudut pandang ini juga mempersoalkan apa sebenarnya yang harus terjadi lingkup (idealistic model). Hal ini juga berkaitan dengan persoalan rekayasa penataan ekonomi yang didasarkan pada cita-cita.
Keempat, model yang akan digerakkan tentu tidak bisa langsung diambil begitu saja dari langit, tetapi perlu didasarkan pada visi. Dalam konteks Indonesia, visinya tentu Pancasila. Model demokrasi ekonomipun rupanya semacam praxis (ungkapan nyata dari visionary entity) yang muncul dari dasar negara dan UUD 1945. Kerena, normative economy dilandasi oleh pandangan dasar kita.
Paradigma Pareto Optimum dalam teori ekonomi memaklumkan bahwa kepuasan yang digapai seseorang hendaknya tidak boleh mengorbankan kepuasan orang lain. Hal ini amat rapat pertaliannya dengan paham keadilan sosial dalam Pancasila. Pareto Optimum itu di beberapa tempat dalam praktiknya dapat mempengaruhi para pelaku ekonomi supaya tidak serakah dan mengubah pandangan tentang tujuan ekonomi (economic goals) agar tidak selalu dalam lingkup untuk mencari untung semata, tetapi dilihat dalam konteks yang lebih luas bagaimana menggerakkan efisiensi, pemerataan pendapatan, keadilan harga (justum pretium), perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Berkaitan dengan itu, muncul pula pandangan yang mempersoalkan tentang insentif ekonomi yang digerakkan melalui pasar atau mempengaruhi pasar tetapi di dalamnya juga memiliki kepekaan yang mendasar kepada kepentingan masyarakat luas, rasa keadilan, rasa tanggung jawab dan etika berinteraksi dalam memacu kegiatan-kegiatan ekonomi. Cukup banyak negara yang merekayasa kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan protective serta preservation scheme dan anti monopoli atau pembatasan kolusi dan pencegahan supernormal profit dari pada monopolis. Kebijakan ini juga mendasarkan diri pada berbagai hal yang berkaitan dengan keadilan.
Kelima, ekonom yang peka pada keadilan sosial dan pemerataan juga membicarakan tentang permodelan (Modeling the economy) yang di dalamnya mempersoalkan secara terus menerus tentang aneka kebijakan (macro and micro policies) yang erat kaitannya dengan tujuan ekonomi yang luas seperti yang dipaparkan tadi.
Bahkan secara amat tajam mereka mempersoalkan tentang penghindaran biaya sosial (social cost) oleh para pelaku ekonomi untuk mencapai tujuan ekonomi atau melakukan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. The Modeling Economy direkayasa untuk memacu social audit dalam tingkah laku berekonomi untuk memaksa kapitalisme yang tidak manusiawi supaya menjadi pro people capitalism. Modeling tadi juga memasukkan atau mempersoalkan aneka upaya yang dipacu untuk meninggalkan praktik-praktik serakah yang merugikan kepentingan rakyat banyak, namun tanpa meninggalkan penataan insentif dalam aktivitas ekonomi. Rasanya permodelan ekonomi versi Indonesia perlu dipacu bersama secara relevan dengan kepekaan tertentu. Permodelan dalam kerangka mewujudkan demokrasi ekonomi perlu direkayasa sesuai konteks yang berlandaskan visi ekonomi. Berkaitan dengan itu, dibutuhkan dialog yang intens dan sikap terbuka.
Keenam, berkaitan dengan aneka rekayasa di atas, sering dibicarakan pula tentang koperasi, seperti di Jepang dan Korea dengan peran koperasi yang begitu kuat yang mulai memunculkan sosok tulang punggung perekonomian negara bukan tulang jari kelingking. Bahkan penggerak koperasi di Jepang seperti Kagawa mempersoalkan brother hood economy atau paham kekeluargaan dalam berekonomi yang menjadi dasar koperasi sehingga koperasi di negara itu juga menjadi agen dari demokrasi ekonomi.
Pandangan almarhum Moh. Hatta dan Kagawa dalam banyak hal adalah sama, bahwa koperasi harus dibangun mulai dari bawah dan kemudian harus menjadi besar. Karena anggota koperasi adalah pemilik dan pengguna dari kegiatan koperasinya, maka ia perlu direkayasa untuk menjadi besar dan kuat.Bukan seperti yang dikehendaki oleh Kwik Kian Gie (tertulis di Harian Kompas) yang menginginkan koperasi tetap mengurus yang kecil saja. Karena, normative economy itu diarahkan oleh pandangan dasar kita yang muncul dari dasar negara dan UUD 1945.
Sumber: Keuangan LSM